Episode 1 novel Rahmah El Yunusiyyah
Ini adalah episode 1 novel Rahmah El Yunusiyyah. Untuk baca selengkapnya bisa pesan di marketplace Toko Buku JS Khairen.
2/20/20265 min read
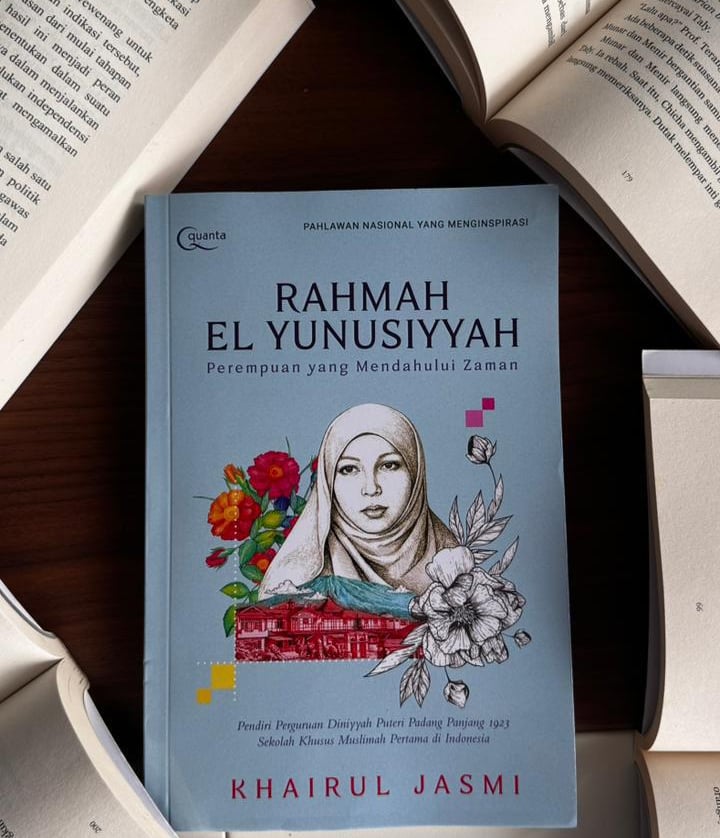
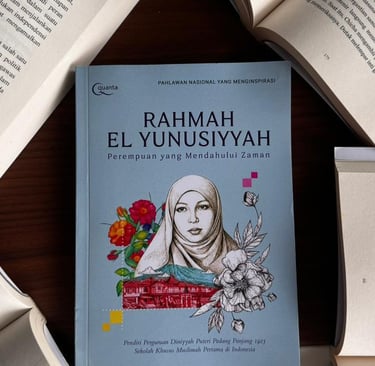
EPISODE 1 - GERHANA MATAHARI TOTAL
pagi jatuh lembut dalam pelukan lembah-lembah di Padang Panjang, sejuk telah berputik pada tangkai waktu yang belum sempurna. Fajar memulai kisah. Inilah pagi, yang berangsur sibuk di pancuran, tempat air selalu mengalir tak henti siang dan malam. Lalu cahaya matahari berpendar jinak, menyapu dengan sempurna kota ini, memberi sinar ultraviolet pada setiap orang. Hidup dimulai. Inilah kota dingin, dipagut tiga gunung, kota yang sedang riuh oleh dunia pendidikan dan perdebatan intelektual kaum terpelajar.
Hari ini bukan soal itu, tapi tentang sebuah pemandangan yang ganjil. Tak lazim. Sebentar saja setelah pagi menyulam waktu menuju siang, segalanya berubah, langit berangsur bu- ram, matahari sumbing sedikit demi sedikit. Lalu, tertutup bulan. Inilah Gerhana Matahari Total. Langit mulai merona, korona mengenggam kisah pahit kehidupan. Matahari tergayut tak bertampuk di langit tua. Kelelahan. Rakyat di kota Padang menengadah ke langit. Beberapa ahli dari Amerika, di pacuan kuda Tabing, memasang alat pemantau yang oleh rakyat di- sebut perkakas tukang nujum.
Hari yang sama di Bukittinggi, gerhana terjadi di tengah langit yang cerah. Sama halnya di Padang Panjang, kota kecil yang terpaut sekitar 70 km dari Padang, warga berbondong keluar rumah. Mereka takjub melihat gerhana yang sayup- sayup. Hari itu, Sabtu, 18 Mei 1901, matahari dihalangi bulan, membentuk rupa menyeramkan. Entah apa yang akan terjadi. Langit seolah dibentang malaikat. Ini dimaknai sebagai peringatan dari Tuhan melalui fenomena alam. Lalu, sejumlah ulama di Jembatan Besi kota dingin itu, melaksanakan Salat Gerhana Matahari.
Saat gerhana itu, Padang Panjang berkabut tipis. Seorang ibu tak turun. Ia menutup semua pintu. Di rumah itu, seorang bayi perempuan berusia lima bulan, menggeliat karena ayun- annya melambat. Ayunan itu digayutkan dengan memakai dua tali ijuk, mungkin buatan Pasir Laweh, kaki gunung Marapi, Tanah Datar. Ayunan itu dianyam dari bambu, buatan orang Singgalang, tak jauh dari Bukit Surungan, dekat sekali ke Lubuk Mata Kucing, rumah di tempat mana si bayi sedang di- buai—ditidurkan. Ia terlihat lelap, kepalanya terletak di atas bantal kecil nan empuk, berisi kapas dari tepian Singkarak.
Bayi perempuan itu bernama Rahmah. Sekarang belum waktu- nya ia bisa mengerti gerhana. Tak seorang pun yang tahu masa depan anak ini, tapi kelak ia telah digariskan akan membuat bangsanya tercengang, bak warga Padang Panjang kagum melihat gerhana siang ini. Ayah Rahmah, Muhammad Yunus al-Khalidiyah, seorang ulama terkemuka, turun dan mencium bayinya yang sedang diayun.
“Dia tertidur,” katanya, menatap istrinya.
“Iya, tadi menangis saja, lelah dia,” kata sang istri. “Sudah disusukan dia?
“Pergi sajalah Buya, itu kerja saya, apa Buya tak melihat tadi?” Istrinya “mengusirnya” untuk segera pergi salat.
“Iyalah, saya kan hanya bertanya. Assalamualaikum,” Yunus meluncur turun, sedangkan istrinya, tersenyum tipis. Ia akan bertanak untuk suami dan empat anak lainnya. Zainuddin, anak tertua, ikut ayahnya Salat Gerhana, yang tiga lain sedang bermain. Anak-anak itu menyapa Buya kepada ayahnya, se- mentara ibu dipanggil Umi.
Rahmah kembali diayun, ia makin lelap. Rafiah memandang anak bungsunya. Suaminya yang alim, memberi nama anak mereka “Rahmah” yang artinya kasih sayang. Nama itu pantas dilekatkan pada si bungsu. Rafiah teringat saat kelahiran bayi- nya, Sabtu, 20 Desember 1900. Tak terasa sudah lima bulan saja usia Rahmah.
Ketika melahirkan, ia berjuang melawan maut. Kala itu, cuaca dingin, gerimis halus sedang turun, melayang disapu angin yang muncul dari arah lembah Lubuk Mata Kucing. Nyaris senyap, yang terdengar desau air di anak sungai, juga napas Rafiah. Kakaknya, Kudi Urai, yang bidan itu, membantu proses kelahiran.
“Tarik napasmu, tarik, terus, terus….”
Tubuhnya terasa nyeri yang amat sangat, semua persendian seakan mau putus, perutnya berkali-kali lipat lebih nyeri. Tak terkatakan.
“Buya Yunus, jangan jauh-jauh, tapi jangan terlalu dekat,” kata Kudi Urai. Pria itu tak menjawab. Ia gelisah, tiap sebentar memandang keluar, yang tampak gerimis bagai embun yang liar disapu-sapu angin. Ia memegang keempat anaknya yang belum mengerti apa-apa.
Kudi Urai sudah berkeringat, punggungnya basah, sementara Rafiah jangan disebut lagi, sudah mandi oleh peluhnya. Yunus yang syekh itu, juga berpeluh padahal hari sedang dingin. Di sini, di kasur ini, setelah melakukan perjuangan yang amat keras, proses persalinan selesai. Tangis seorang bayi pun pecah. Rafiah terkulai tak berdaya. Ia amat lelah, tetapi hati- nya bahagia tatkala ada tangis yang terasa bagai suara dari surga menyiram seluruh tubuhnya. Bayi itu pada beberapa bagian tubuhnya berdarah, bidan segera memotong tali pusar, memberinya obat dan menutupnya.
“Ini, kau peluklah anakmu,” kata bidan. Rafiah memeluknya. Ia bawa si anak dan ditidurkan di atas tangannya, kemudian didekap ke dada. Kulit bertemu kulit. Rafiah sendu, matanya sabak. Ia menangis. Air mata itu jatuh di kening si bayi. Ini proses amat alami, memperkenalkan anak pada ibunya melalui sentuhan kulit. Si bayi yang tadi menangis, kini sudah tidak, proses kehangatan sedang mengalir. Proses perkenalan dunia di luar rahim sedang berlangsung. Ia mendekap bayi- nya, merasakan detak jantung bayinya yang memerlukan kehangatan dari kulitnya. Ia merasakan ada yang menyapanya sayup. Amat sayup.
Dalam waktu yang amat singkat, tatkala si bayi masih di- dekap, ia teringat sebuah kampung di Ampek Angkek, Agam. Dari sana nenek moyangnya turun ke Padang Panjang, awal-awal abad ke-18. Ingatannya juga mampir ke Pandai Sikek, desa yang bersandar ke kaki Gunung Singgalang. Dari sanalah suaminya berasal. Ia teringat Haji Miskin, pria gagah perkasa yang tak tertirukan itu, adalah paman Syekh Yunus, suaminya. Darah ulama mengalir pada Rafiah. Tak tahu kenapa pikirannya melayang begitu cepat ke sana.
Rafiah mencium kening anaknya. Si bayi sudah sedu sedan. Ia melayangkan pandangannya, ternyata di sebelah telah duduk sang suami.
“Buya sudah berwudu?” tanya Rafiah. “Sudah.”
“Ikamah-lah,” katanya sembari menyerahkan bayi yang baru lahir itu kepada suaminya.
“Tunggu,” kata bidan Urai. Ia kemudian mengambil bayi itu, membersihkan dan membalutnya dengan kain panjang ter- baik, lalu ia serahkan pada Yunus.
Pria itu, bersimpuh, kemudian berdiri dan menghadap kiblat. Ia ikamahkan anaknya di telinga kanan. Tak lama, selesai. Bayi kemudian diambil bidan untuk diurus.
Lamunan Rafiah putus ketika si bayi merengek di buaian. Ia tersentak. Ia menjujai1, tapi tak ada gunanya, sebab si bayi kini malah menangis.
“Rahmah, kenapa menangis sayang?” Tak ada gunanya juga. Ternyata selimutnya sudah basah. Rafiah segera mengangkat Rahmah, meletakkannya di lantai, menukar pakaiannya, mengganti selimut dan alas ayunan. Walau begitu, Rahmah, bukannya diayun, tapi digendong. Bayi itu tersenyum, lalu digoda, tersenyum lagi.
1 Tindakan menggoda balita agar si bayi terhibur.
Ini Sabtu yang ganjil, gerhana cincin sudah selesai. Sekejap saja. Bayi ini sudah punya kemampuan motorik, ia berguling, telentang dan tengkurap, meski dengan susah payah. Setiap diimbau, ia menoleh, sesering dijujai, ia tersenyum. Kadang “keras” perutnya akibat tertawa karena terus digoda uminya.
Sang ibu kemudian bergumam, ia membaca nazam yang ia karang sendiri dalam dendang yang syahdu:
Jika engkau sudahlah besar Dekatkan diri pada Allah yang Akbar Berusaha di dunia haruslah sabar Biar ke jalan surga menjadi lancarWahai anak pedusi umi
Si bungsu tak beradik lagi Jangan lupa ayah dan umi
Apalagi agama Islam sudah terpatri Disebut orang di seluruh negeri
Jika ayah umi tiada
Engkau empat punya saudara Dunsanak banyak di mana-mana Takkan susah engkau di dunia
Nazam karangan sendiri itu terhenti ketika daun pintu dibanting angin senja. Tak lama kemudian, magrib jatuh di Padang Panjang, kelelawar terbang entah ke mana, bedug bertalu-talu. Semua pintu di semua rumah ditutup. Malam akan menyelimuti kota ini dengan sempurna. Kesempurnaan itu dikawal angin dingin dari tiga gunung sekaligus, Tandikat, Singgalang dan Marapi.
Zainuddin, anak tertua, segera mengaji selepas magrib, sedang- kan adik-adiknya, Mariah, Muhamamd Rasyad dan Rihanah, ikut juga duduk dekat umi mereka yang mengajar mengaji. Rahmah sudah tertidur di kasur kecil di kamar uminya.
Zainuddin sendiri hampir 10 tahun lebih tua dari Rahmah. Pria itu lahir pada Sabtu 21 Februari 1891 atau 12 Rajab 1308 H. Pada hari yang sama, seorang ibu bergegas meninggal- kan stasiun kereta api di Silaing, padahal tadi ia hendak memperhatikan dekat-dekat sejumlah pejabat Belanda yang baru tiba. Tetangganya melahirkan, ia harus ada di sana, tapi ia justru terlambat, seorang bayi laki-laki sudah lahir. Tak lama kemudian, hanya beberapa hari, bayi itu diberi nama Zainuddin.
Wanita itu, sebenarnya tak perlu benar-benar bergegas, tapi hatinya tak enak. Sebab baginya, tetangganya itu, Rafiah, sudah seperti kawan sendiri. Kemarin, ia ke pasar membelikan stagen baru warna merah hati untuk Rafiah. Ia ke stasiun baru itu karena ingin mendapatkan cerita dari pandangan mata sendiri, betapa orang sibuk membangun rel dan jembatan serta stasiun kereta. Kabarnya sekitar empat bulan lagi akan siap dan kereta akan lewat menuju Sawalunto, menjemput batubara di sana. Apa itu batubara, ia tak tahu. Tahun kelahiran Zainuddin sama dengan melajunya kereta api di Padang Panjang: 1891.
✽✽✽