Episode 1 Buku Rinduku Sederas Hujan Sore Itu
Ini adalah episode 1 buku Rinduku Sederas Hujan Sore Itu. Untuk baca selengkapnya bisa pesan di marketplace Toko Buku JS Khairen.
2/6/20267 min read
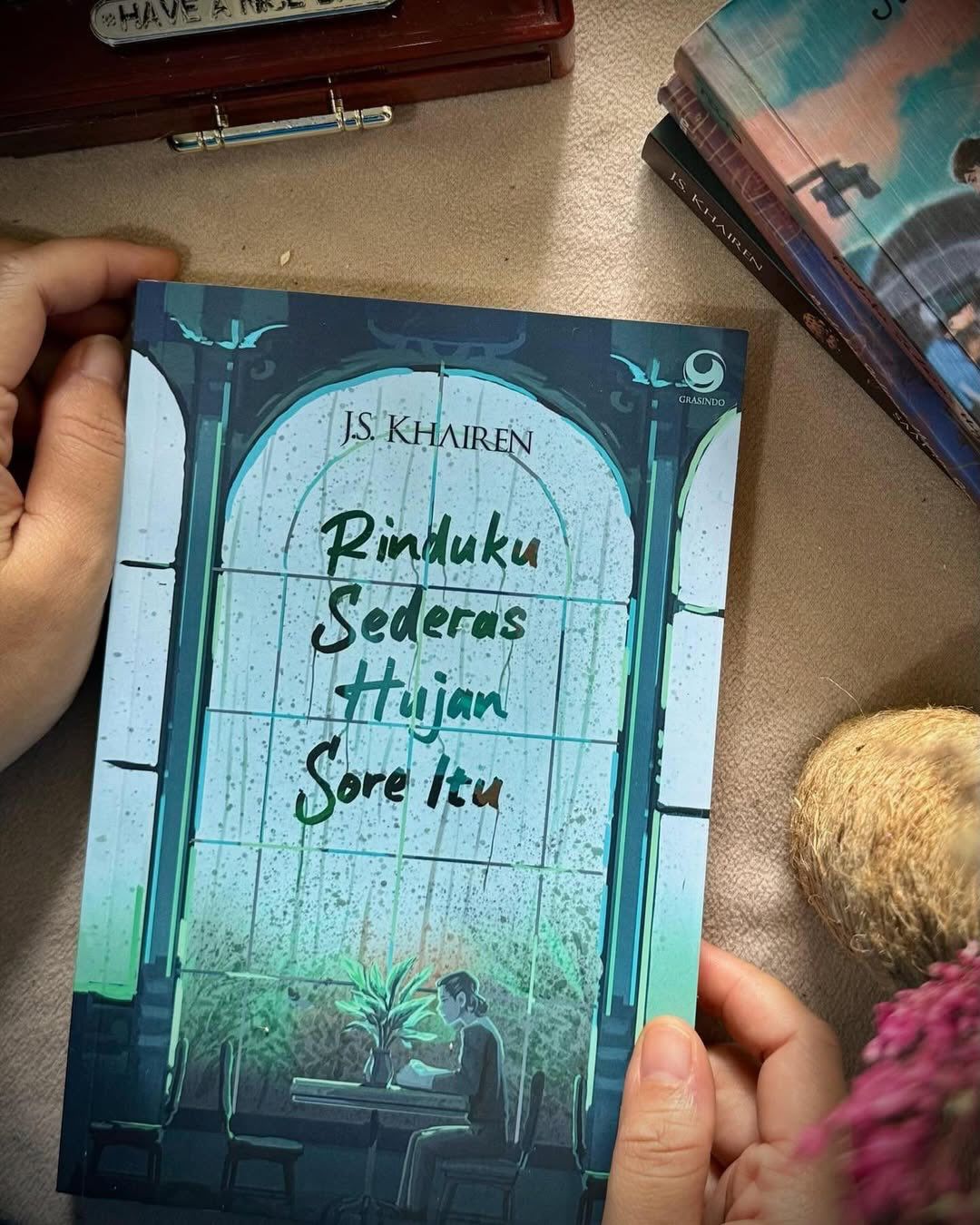
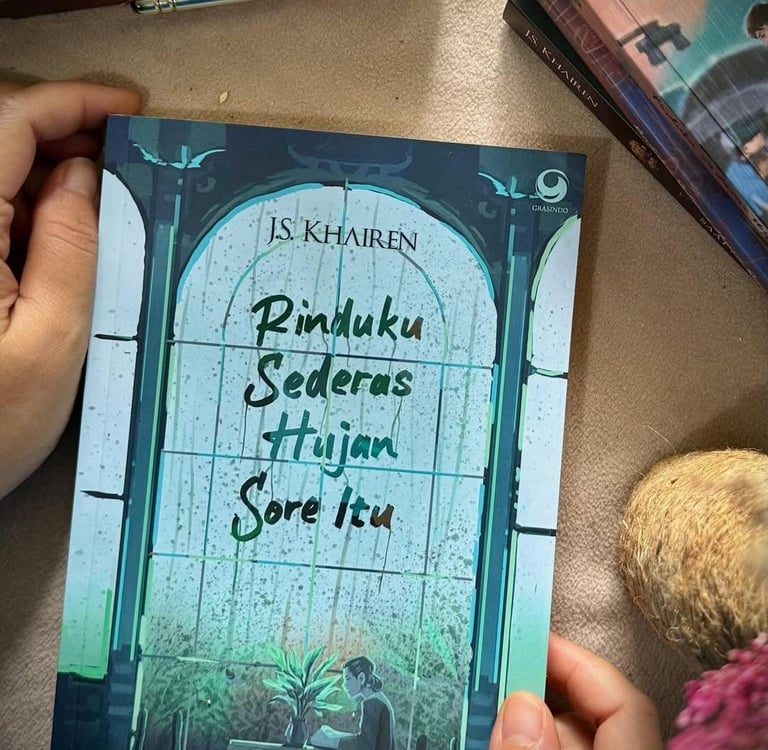
DO[S]A
Apakah langit berdusta pada tiap doa?
Apakah bumi khianat dan memeluk semua dosa?
Apa alasan Sang Mahapasti menciptakan benci dan cinta?
Aku tak pernah mengenal Ibu. Bagiku Ayah adalah keduanya; ayah sekaligus ibu. Wajah wanita itu hanya aku lihat sekali. Di foto pernikahan yang tergantung di kamar Ayah, yang sejak SMA, aku minta Ayah untuk tidak menggantungnya lagi di sana.
Ibuku tidak meninggal saat melahirkanku. Saat ini, dia masih hidup. Aku tahu Ayah sesekali masih berjumpa dengannya. Aku tak pernah mau ikut. Apakah Ibu meninggalkan Ayah, bercerai, atau ada situasi khusus? Aku tak tahu.
Usia 3 Tahun.
Ini petualangan pertama dan terjauhku bersama Ayah. Ayah mengajakku ke Jakarta. Naik pesawat dan telingaku disumbat kapas. Kata Ayah, “Supaya tidak sakit.”
Aku dibawa ke Ancol dan main apa saja yang aku mau. Terpekik-pekik aku dibuatnya ketika merasa seakan mau jatuh. Paling lucu yang aku ingat, Ayah terpaksa membawaku ke toilet laki-laki karena tidak mungkin Ayah menemaniku di toilet wanita. Wajah Ayah tampak panik sekaligus malu saat itu.
Dan, yang paling seru adalah ketika bermain arung jeram. Kapalnya aneh. Terbuat dari plastik dan bundar seperti donat, tetapi tidak bolong di tengah. Sewaktu naik, badanku masih kering. Ketika turun, basah semua.
Dan, tidak ada Ibu.
Usia 5 tahun.
“Cantiknya Ayah mana? Sini, sini, Ayah pasangin baju.” Kemudian, aku menggenggam rambut hitam Ayah yang berjongkok di depanku sehingga tubuhku leluasa dan seimbang untuk memasukkan kedua kaki ke rok sekolah.
“Pinteeer.” Ayah mencium pipiku. “Sekarang sepatunya, ya, Cantik.”
Mataku masih mengantuk. Namun, tiap kali Ayah menyebutku cantik, makin terkumpul nyawaku, makin hilang kantukku.
Ayah mencemongkan bedak di wajahku. Kadang rata, seringnya berantakan. Ayah melakukan semuanya, mulai dari memandikanku, menyiapkan sarapan, hingga mengantarkan- ku ke TK. Di gerbang TK, Ayah melepasku dengan senyum dan lambaian tangan.
Teman-temanku kebanyakan diantar para ibu. Atau, bahkan oleh kedua orangtua sekaligus. Namun, aku tak pernah sedih karena ayahku berperan sebagai ayah sekaligus ibu. Lebih dari itu, Ayah selalu membelikanku dua permen gulali. Sedangkan yang lain, ada yang hanya dibelikan satu, ada yang tidak dibelikan sama sekali. Jadi, biarlah mereka diantar ibu mereka, yang penting aku dapat gulali. Ayahku paling hebat, pokoknya.
Begitu jam pulang, Ayah akan mengajakku berkeliling kota kecil kami. Naik angkot yang hanya ada empat kali sehari, dengan rute bolak-balik ke desaku.
Dan, tidak ada Ibu.
Usia 7 Tahun.
Ini pertama kali Ayah mengajakku ke bioskop. Aku takjub luar biasa melihat layar televisi yang begitu besar. Sejak saat itu, aku suka film kartun yang bercerita tentang tuan putri. Aku menjadi tuan putri, di mana Ayah adalah rajanya. Kami tidak memiliki ratu.
Sepulangnya kami, Ayah langsung membuatkanku gaun dari bahan-bahan alam. Bukan gaun sutra dan permata, melainkan dedaunan dan batok kelapa yang membalut tubuhku. Sudah seperti tuan putri kerajaan rimba.
Sesekali, Ayah membawaku duduk di dahan pohon, menunjuk Bukit Barisan sambil berkisah apa saja yang Ayah ingin ceritakan. Sore hari, jika itu Minggu, Ayah akan membawaku naik bianglala di pasar malam. Aku adalah tuan putri bagi Ayah di kerajaan kecil kami.
Dan, tidak ada Ibu.
Usia 16 Tahun.
Aku mulai suka membaca novel. Sebulan, aku bisa menamatkan dua hingga tiga novel. Aku meminjamnya di perpustakaan sekolah, kepada teman, atau di tempat penyewaan buku dekat pasar. Sehari, dua ratus rupiah biaya pinjamnya. Aku tak pernah lebih dari lima hari menyewa sebuah novel. Lebih dari seribu saja sudah mahal rasanya. Juga karena aku begitu cepat menamatkannya.
Beberapa blok dari penyewaan buku itu, ada rental Internet. Masa SMA juga menjadi masa pertama kali aku mengenal Internet. Sekotak layar membuatku tenggelam dalam dunia amat luas. Tak terbayangkan ada sesuatu selain buku yang membuatku terbang bersama banyak hal.
Aku pergi bersama tiga-empat teman sekelas dan menyewa satu komputer untuk dipakai bersama. Kami semua membuat akun di Friendster. Melihat-lihat orang di luar sekolah kami, di luar kota, di luar provinsi, bahkan di luar negeri. Ternyata, bumi ini tak seluas kampungku saja.
Pada usia ini, aku mulai bertanya, dan merindukan, dengan jauh lebih serius, siapa Ibuku. Di mana dia sekarang, apa yang sedang dia lakukan, dan mengapa dia pergi? Apa kah Friendster bisa mempertemukanku dengan Ibu?
Masa remajaku terlewati tanpa kehadiran Ibu. Aku ingin dipeluk oleh seorang ibu, tetapi tak pernah. Doaku tak didengarkan langit. Aku muak!
Oh, ya, pada usia ini pula aku pertama kali disentuh lelaki. Hanya bergandengan, usap-usap rambut, dan satu kecupan kilat di kening. Namun, terasa begitu lama dan entah mengapa aku menikmatinya. Aku jatuh cinta. Sensasi baru yang aku rasakan dalam hidup. Kilat dan nikmat. Mungkin, bila ada Ibu di sisiku, dapat aku curahkan semua perasaan ini.
Dia kakak kelas yang dua bulan mondar-mandir di depan kelasku. Kemudian, lewat temanku, kami diperkenalkan. Dia berani-beraninya masuk ke kelasku, menipu guru bahwa dia adalah siswa kelasku, dan duduk di sebelahku. Tidak ada yang komplain. Ini yang dia lakukan tiap dia rindu, katanya.
Pulang jam olahraga, dia ternyata menunggu dan dengan kerubungan teman-temannya, dia menyatakan cinta kepa- daku. Awalnya aku takut, malu sekali. Akhirnya, aku terima. Hal ini aku rahasiakan dari Ayah.
Usia 22 Tahun.
Aku gagal menjadi tuan putri. Namun, aku baru saja menjadi dokter.
Hari wisuda, Ayah datang bersama seorang wanita yang kemudian memelukku secara tiba-tiba. Aku tahu itu Ibu, tak mungkin ada orang gila yang begitu saja langsung memeluk orang yang tidak dia kenal.
Dalam hati, saat dipeluk, aku marah, sedih, bahagia, semua bercampur. Ternyata, ketika aku perhatikan, bola matanya sama denganku.
Kaukah ibuku? Ke mana saja engkau? Meninggalkanku sejak aku bayi? Aku tak pernah merasakan cinta ibu dan sekarang, kau datang pada hari wisudaku? Bahkan, ilmu dokterku tak bisa menjelaskan perasaan macam apa ini. Antara ingin memeluknya hingga terbunuh atau menciuminya hingga tertawa muak.
Aku benci sekali suasana kikuk seperti ini. Sebenarnya, sejak SMA, aku tidak lagi mempertanyakan kondisi keluargaku. Jika ada yang bertanya tentang Ibu, aku sudah datar dan biasa saja. Namun, pada hari wisuda ini, aku hancur.
Ternyata, mereka terpaksa bercerai. Restu kakek nenekku tidak mereka dapatkan. Ayah dan Ibu saling mencintai, tetapi mereka berbeda. Tidak mungkin dan tidak bisa menjadi pasangan suami istri. Pencipta langit mereka berbeda, penerima doa mereka berbeda, cara mereka menyambut takdir berbeda.
Ketika aku melepas pelukan orang yang kemudian kupanggil Ibu, aku melihat selingkar kalung salib di lehernya. Ini penyebabnya. Ayah tak pernah menceritakan ini kepadaku. Kenapa dia menyembunyikan ini dariku?
Aku mencoba menerjemahkan asa yang selama ini tertanam dalam jiwa kedua orangtuaku. Meringkuk dalam lara. Kata kerja, tanda baca, ucapan sapa. Nihil. Aku tak menemukan kesimpulan. Tak ada yang berhasil keluar satu pun dari bibirku.
Gulungan tikar berdebu disiram cahaya. Lekat pekat suara yang tak pernah terucap. Tak pernah diperdengarkan. Betul-betul menggelinjangkan bak pencinta sayuran tiba-tiba melihat isi piringnya berubah wujud. Seperti itulah rasanya ketika aku melepas pelukan Ibu.
Bagaimanapun, dia ibuku. Dia adalah wanita yang diperjuangkan ayahku mati-matian. Namun, apa hendak dikata, Pencipta Kematian tak menghendaki hubungan mereka.
Sekarang, sudah ada Ibu, tetapi tetap tiada.
Siapa yang paling berdosa di antara doa kami? Aku? Ibu? Ayah?
Aku, aku tidak tahu harus menyalahkan siapa. Dua puluh dua tahun hidupku, yang membutuhkan Ibu, tetapi Ibu tak pernah ada. TIDAK PERNAH ADA! Setetes kehangatan cinta ibu, kata orang, tak pernah aku sesap.
Haruskah aku membencinya? Haruskah aku mencintai nya? Harusnya, ini hari paling bahagiaku. Namun, kecamuk ini seperti badai di Samudra Pasifik yang terus membesar selama dua puluh dua tahun dan kini ia menghampiri daratan, memorakporandakan semuanya.
“Nak,” sapa wanita yang katanya adalah ibuku itu dengan lirih.
Aku tersenyum, tetapi hatiku menggeleng. Menahan- nahan sesuatu di ujung mata dan bibirku. Dia membiarkan Ayah selama ini berjuang sendirian, membesarkanku, mencintaiku, merawatku.
Usia 26 Tahun.
Sudah empat kali sejak kelulusan aku bolak-balik Indonesia Hong Kong untuk bertemu Ibu. Ini semua aku lakukan karena ingin mengambil semua kisah, memori, nasihat, saran, atau apa pun itu namanya dari seseorang yang katanya adalah ibuku. Melihatnya seperti melihat versi penakut diriku.
Kali kelima, aku tidak datang sendirian. Aku datang dengan suamiku. Ibu tidak bisa hadir pada hari pernikahan kami. Jika Ibu hadir, sereng mata semua orang akan menghakimi dan menghadapkan dosa besar kepadanya. Di keluarga besar, Ibu adalah jahanam paling berdosa. Dia tak berhak hidup di bumi ini. Dia tak berhak menerima cinta Ayah. Dia tak berhak melihat anaknya bersanding.
Dalam perjalanan rutin tiap tahun ke Hong Kong, keping-keping keibuan yang harusnya aku dapatkan sejak kecil, aku borong semua sekarang. Awalnya agak kaku, tetapi emosiku bisa menyesuaikan.
Andai kata ketika naik pesawat Ibulah yang menutup telingaku dengan kapas. Andai kata Ibulah yang menemaniku ke toilet wanita. Andai kata Ibulah yang membangunkan, memandikan, dan mengantarkanku ke sekolah. Andai kata di rumah mungil kami lengkap raja dan ratu. Mungkin sekarang aku sudah punya dua atau tiga adik pangeran.
Semua masa lalu yang hanya bersama Ayah, aku rombak dalam pikiranku. Sejarah andai kata. Andai kata waktu itu ada Ibu, apa yang akan terjadi, akan seperti apa aku sekarang.
Usia 32 Tahun, Hari Ini.
Sekarang anak gadisku masuk TK pula, dan tiga minggu setelah itu ayahku, jagoanku, pahlawanku, satu-satunya orangtua yang membesarkanku, dipanggil ke langit oleh Pencipta Cinta.
Meski Ayah telah wafat, aku tidak berhasil memaksa Ibu untuk tinggal bersama kami. Namun, suamiku berhasil. Itulah dia, yang selalu tahu cara melengkapiku. Hanya dengan satu kalimat, Ibu langsung menurut.
“Ibu, Ibu berhak merasakan kehidupan ini,” kata suamiku.
Sudah. Sesederhana dan sesingkat itu. Ibuku langsung mengepak kopernya. Sementara aku, sudah lelah membujuk bertahun-tahun, dan Ibu tetap tak mau.
Setelah Ibu datang, kami mendapat kesempatan kedua. Ibu mendapat kesempatan kedua untuk menjadi Ibu, aku mendapat kesempatan kedua menjadi anak.
“Begitulah ayahmu, kalau bukan dia, mungkin kamu tak- kan sehebat ini sekarang.” Ibu berbicara seakan dia tahu betul detail apa yang aku lalui bersama Ayah.
Aku hanya tersenyum. Andai sejarah terputar kembali.
Pernikahanku, bukan karena aku sangat bergantung kepada laki-laki. Ayah telah membangun kemandirian anak
gadisnya ini. Jika hanya butuh laki-laki untuk membiayai hidup, aku tak perlu. Aku menikah pun bukan karena hendak menggantungkan hidupku kepada laki-laki, melainkan benar- benar karena cinta dan doa. Salah satunya untuk memperbaiki apa yang Ayah dan Ibu sesali dalam hidup. Aku menikah karena ingin membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Aku menikah karena diriku sendiri.
“Ibu tahu Ibu salah, Ibu berdosa. Maafkan Ibu, ya, Nak.” Ini adalah kalimat yang terlontar setiap kali kami selesai mengobrol. Setiap itu pula Ibu menangis. Selepas itu, Ibu akan pergi ke gereja. Entah melanjutkan tangisan atau berdoa. Malamnya, aku sujud lama di atas sajadah.
Kami membawa Ibu ke rumah masa kecilku. Wajah Ibu yang sudah tua, tak bisa menyembunyikan kesedihan. Sekarang ini, usiaku sudah lebih tua dibanding ketika dahulu Ibu meninggalkanku.
“Di sini?” tanya Ibu.
“Ya di sini.” Aku menunjuk rumah sederhana yang sekarang kiri kanannya sudah penuh rumah lain.
Kalimatku tertahan. Tetesan air hangat mengalir di pipi Ibu. Mungkin jawaban di sini bagi Ibu adalah di sini Ayah menjadi Ayah, di sini juga Ayah menjadi Ibu.
Aku tidak mau menjawab seperti itu karena hanya akan memperdalam luka Ibu. Bagaimanapun, dia ibuku. Seperti apa pun dosa Ayah dan Ibu, mereka tetap orangtuaku.
Doaku, hari ini diterima langit. Kami bersatu dalam rumah ini walau Ayah tak lagi ada. Namun, aku merasakan kehadiran Ayah, setiap detik.
Kami menang. Cinta pemenangnya. Sebuah kemenangan mutlak yang tanpa harus kehilangan apa pun dan tanpa harus mengalahkan siapa pun, terjadi ketika tak takut lagi kehilangan hal yang amat dicintai.
Ayah, kalau kau mengintip dari sana, kirimlah senyum barang setangkai ke sini. Aku dan Ibu sudah bahagia.
Rongga langit Batu, 9 Oktober 2015.